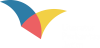“Hati membutuhkan waktu lebih banyak untuk menerima apa yang sudah diketahui pikiran.”
Iya, iya, aku sudah paham.
Kalau saja aku tidak ingat seberapa besar jasa bu Sara dalam persalinan waktu itu, kalimat tadi mungkin sudah terpeleset keluar dari bibirku. Bagaimana tidak, dalam kurang dari dua puluh menit kami berbincang, rasanya sudah lebih dari dua puluh kali ia mengucap kalimat itu. Bahkan saat mengantarku keluar dari halaman rumahnya pun, kalimat yang sama terucap lagi.
Tapi ya sudahlah, pokoknya sekarang aku sudah keluar dari perbincangan tak menyenangkan itu, dan bisa segera pulang untuk menyiapkan keperluan Avi, anak manis kesayanganku nomor satu–dan memang satu-satunya. Anak ajaib yang juga merupakan bukti hidup dan nyata betapa Tuhan menyayangiku.
Setelah dua belas tahun menikah dan terus menanti kehadiran anak, ia datang secara tak terduga kala kami mulai asing dengan harap. Kehadirannya sungguh membawa perubahan besar. Alasan untuk bangun di pagi hari, untuk melakukan berbagai pekerjaan, untuk berjuang, untuk bertahan dalam hidup ini, dalam pernikahan ini, semua bermuara pada Avi. Begitu pula dengan ragam gejolak amarah, tawa, sedih, bahagia, semua berasal dari satu sumber: Avi, yang bahkan ukuran tubuhnya masih belum ada seperempat dari tinggi badanku maupun Elior, suamiku. Kadang kami heran bagaimana bisa makhluk sekecil itu membawa perubahan sebesar ini bagi hidup kami.
“Kenapa menyiapkan cabai?” aku sedikit terganggu melihat Elior membersihkan cabai di tengah kegiatan memasakku.
“Sepertinya masakan ini akan lebih enak kalau pedas,” Elior tertawa kecil sambil membawa beberapa buah cabai yang sudah dicucinya.
“Avi kan belum bisa makan pedas,” bagaimana bisa hal sepenting itu dilupakan? Bagaimana kalau nanti mulut Avi memerah dan ia menangis karena tak sengaja menggigit cabai?
“Oh?” Dia tampak mematung sejenak, kebingungan, lalu menatapku lama. Kenapa? Apa yang salah? Bukankah justru dia yang salah karena hampir memasukkan cabai? Kenapa menatapku begitu?
“Bagaimana kalau bantu siapkan bajunya saja? Untuk berjaga-jaga kalau hujan dan bajunya kotor, kita bawakan pakaian cadangan,” suasana aneh itu (terpaksa) mereda, dan Elior segera meninggalkan dapur.
Masakan sudah matang dan selesai dikemas, sekarang giliran menyiapkan barang lainnya. Aku ingat Avi sangat suka dengan buku bergambar, alat mewarnai, sampai alat musik–walau semuanya masih berbentuk mainan. Ini satu hal lain lagi yang juga membuatku tak habis pikir tentang Avi. Usianya belum genap dua tahun, namun jiwa artistiknya telah begitu nyata terlihat. Mungkin Tuhan memang benar-benar punya rencana hebat bagi anak ini, karena selain kehadirannya yang ajaib, pertumbuhannya pun ajaib. Semoga kelak ia dapat bertumbuh sebagai anak yang sungguh-sungguh membawa keajaiban bagi orang di sekitarnya, sebagaimana ia telah membawa keajaiban bagi hidupku dan Elior.
“Sayang, apa semua sudah siap?” barang-barang yang sudah kami siapkan tampak berjajar rapi di sisi kiri dan kanan punggung Naba, keledai milik bu Sara yang memang sering dipinjam beberapa orang di perkampungan ini untuk alat transportasi sehari-hari.
Sekali lagi aku memastikan semuanya. “Sudah siap.”
“Apa kau sudah siap?” Elior bertanya lagi, kali ini lebih tegas sekaligus lembut.
“Kapan aku pernah tak siap?”
Jarak dari rumah kami ke tempat tujuan sebenarnya tidak terlalu jauh, namun bukan berarti mudah untuk ditempuh. Sisa jarak yang kian menipis membuat nyaliku turut menipis. Duh, padahal ini bukan kali pertama, namun kekhawatiran yang sama tetap muncul dan terus menggangguku: bagaimana kalau aku tidak kuat?
Tidak, tidak. Aku harus kuat, demi Avi. Aku terus berupaya mengumpulkan kekuatan, sembari memfokuskan pikiranku pada Avi. Tawanya yang meriah, pipinya yang memerah, juga segala tingkah-tingkahnya yang menggemaskan. Oh, tidak! Aku salah mengalihkan pikiran. Kini sesak mulai berkumpul di dada, bahkan mataku pun sudah basah tanpa disadari.
“Mama … kenapa?” kepalaku tiba-tiba menjadi alat yang memutar kaset rusak dan terus mengulang bagian itu. Terus menerus. Berulang-ulang.
Tolong aku.
***
“Kita sudah sampai,” suara Elior menolong, menyadarkanku untuk kembali memproses realita bahwa kami benar-benar sudah sampai. Tanpa banyak bicara ia segera menyalakan obor dan menarik batu besar yang menutup mulut goa, membebaskan udara dingin nan lembab yang entah sejak kapan bersemayam di sana. Tidakkah Avi-ku kedinginan atau ketakutan? Avi-ku, kan, paling takut dengan kegelapan!
Mengingat itu membuatku sedikit panik. Meski lutut ini terasa lemas dan lemah, dengan kekuatan yang tersisa aku berusaha melahap jarak secepat mungkin. Aku ingin segera dekat dengan Avi!
Ayo lari, Nak! Mama datang!
Aku ingin Avi berlari menghampiriku, dengan tawa kecilnya, dengan langkah ringkihnya, dengan tangan mungilnya yang terbuka lebar, dengan manik cokelatnya yang berbinar indah.
Tapi itu hanya ingin.
Karena Avi ada di sana, tapi juga tak ada di sana.
***
Tubuh mungil itu terbujur kaku di antara kain linen yang membalutnya rapi. Wajah itu tetap menggemaskan, meski tampak jauh lebih pucat daripada kunjungan terakhir.
Aku tahu. Aku paham, bahwa ini nyata. Namun sebagian diriku yang lain masih menyimpan harapan konyol. Harapan yang mendorongku menata makanan, mainan-mainan, dan sejumlah barang kesukaan Avi. Harapan yang membuatku mengira mungkin Avi akan terbangun saat mencium aroma makanan favoritnya, mendengar gemerincing mainan kesukaannya. Harapan yang sangat konyol, memang. Aku tahu. Aku paham. Tapi bolehkah aku membiarkan harapan itu ada, setidaknya sebentar saja? Hatiku belum sanggup menerima kenyataan. Mendadak aku teringat dengan ucapan bu Sara. Ternyata benar, hati membutuhkan waktu lebih banyak untuk menerima apa yang sudah diketahui pikiran. Ternyata ini maknanya.
Dalam detik berikutnya, aku hilang kendali. Aku berteriak mengungkap sakit yang tak tergambarkan dalam kata, bahasa, dan suara apapun. Aku menangis menyuarakan pahitnya dahaga rindu yang kutahu mustahil terpuaskan. Avi tak akan pernah bisa digantikan oleh apapun, oleh siapapun.
Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku? Aku masih bernafas, jantungku masih berdetak, kelembutan tangan Elior yang bersandar di bahu pun masih terasa jelas. Namun hidupku seolah telah diambil secara paksa, dan tubuh ini hanyalah selongsong peluru yang kosong, tak berguna.
Sekali lagi aku mulai asing dengan harap.
Tuhan, mengapa?
***
Setelah beberapa saat, aku kembali berjejak pada realita. Elior yang tampak sibuk membersihkan bungkusan rempah-rempah menyadarkanku bahwa di sini baunya mulai kurang sedap, mungkin karena udaranya lembab dan biasa tertutup rapat. Perlahan kekuatanku mulai berkumpul lagi, dan aku membantu Elior berbenah, membersihkan bungkusan-bungkusan rempah yang lusuh, dedaunan kering, lalu menjajarkan rempah-rempah yang baru.
Tak ada yang bersuara, tak ada percakapan apapun di antara kami, namun kepalaku benar-benar berisik, melemparku kembali pada malam mencekam itu.
Malam itu, sudah ada rencana kecil yang hendak kami lakukan. Bukan acara besar, hanya berkumpul di rumah selepas makan malam untuk mendengarkan kisah dari Kitab Suci, lalu berdoa bersama. Elior dengan segala kreativitasnya sudah bersiap untuk menyampaikan cerita Daud melawan Goliat. Dari beberapa hari sebelumnya ia sudah membuat beberapa properti, memikirkan cara supaya Avi dapat terpikat pada cerita, tapi juga tetap memahami maknanya: bahwa Tuhanlah yang bekerja melalui Daud yang saat itu dipandang kecil, diremehkan. Namun belum sebelum makan malam selesai, terdengar keributan besar.
Aku masih ingat betul, malam itu tanah terasa bergetar, apakah ada gempa bumi? Tidak-tidak, ini bukan jenis getaran yang disebabkan alam. Tak berselang lama, suara gemuruh terdengar menyusul. Gemuruh yang disebabkan oleh langkah kaki dalam jumlah banyak.
“Ada banyak prajurit,” Elior mengintip dari jendela, dan berbalik dengan kecemasan di wajahnya. Kira-kira ada apa ya? Tumben sekali ada banyak prajurit di waktu-waktu ini? Apakah ada perang? Atau ada berita penting apa yang hendak diumumkan raja? Aku masih terus berusaha memikirkan hal baik, meski jauh dalam diri mulai timbul perasaan tak enak.
“AAAAA!!!! JANGAN!!!” Jeritan melengking itu terdengar jelas, menusuk telingaku. Tak butuh waktu lama, aku menyadari bahwa kami dalam bahaya. Aku segera menarik Avi dalam pelukan, memaksanya tenggelam dalam kain-kain pakaianku, dan membawanya bersembunyi di lemari.
Avi kecil mungkin menangkap suasana mencekam itu, dan mulai menangis kencang. Sebisanya, aku berusaha menenangkan, sebisanya aku memeluknya erat, namun mungkin lagi-lagi ia peka terhadap ketegangan yang dirasakan orang tuanya, ia terus menangis. Tangisan kencang yang sangat kusesali saat itu, namun sangat kurindukan saat ini.
Aku benar-benar tak mengerti, apa yang terjadi di luar sana? Jeritan apa tadi?
Apa yang para prajurit itu kehendaki? Lalu, bagaimana Elior? ELIOR?!!!
BRAKK!
Aku tak sempat untuk mengecek keberadaan Elior, dan tak cukup berani setelah mendengar dentuman keras, suara pintu yang roboh. Oh, Tuhan, semoga perlindungan-Mu ada bagi Elior.
“Di mana anakmu?!” meski tak melihat, aku membayangkan pemilik suara berat itu bertubuh besar, dan punya raut wajah menyeramkan. Anehnya, tiba-tiba aku tak mendengar apapun. Semuanya mendadak jadi begitu hening, begitu tenang. Kenapa ini? Apa aku tiba-tiba kehilangan indera pendengaranku?
Dari lubang kunci lemari, aku hanya melihat kekosongan. Apa prajurit itu sudah pergi? Apakah sudah aman? Sayangnya ingatanku berhenti di sana, tepat saat aku melangkah keluar dari lemari. Tak ada ingatan lagi selain gambaran tubuh Avi yang tergeletak lemah, memucat, di tengah ruang.
Tuhan, di mana Engkau?
***
“Bagaimana kalau kita segera pulang?” suara Elior menarikku kembali pada realita, ternyata di luar langit begitu gelap, petir mulai samar-samar terlihat. Baiklah, mari pulang. Kami segera berbenah, kembali menata barang yang sama di punggung Naba. Saat Elior sibuk mengurus obor dan batu, mataku menangkap pemandangan hangat sekaligus menyedihkan.
Aku melihat satu keluarga kecil, persis dengan keluargaku–ada ayah, ibu, dan satu anak, dengan keledai dan beberapa perabotan di punggungnya. Raut lelah tampak jelas di wajah suami-istri itu, namun kalah besar dengan sukacita ketika mereka menatap Sang Anak. Anak itu sepertinya berusia mirip dengan Avi, membuatku tak bisa tak melihatnya.
Dadaku kembali jadi ruang bagi kecamuk amarah, kecewa, juga rasa tak terima, kenapa Anak itu selamat sedang anakku tidak? Namun secara bersamaan ada suatu ketenteraman yang entah darimana asalnya dan bagaimana menjelaskannya, aku tak tahu, yang pasti itu meliputi, menguasai hatiku, meski kekecewaan masih jelas ada. Aku bahkan baru tahu bahwa perasaan-perasaan ini bisa muncul bersamaan.
“Memang, seringkali hati membutuhkan waktu lebih banyak untuk menerima apa yang sudah diketahui pikiran, ya,” Elior berucap tepat saat kami memulai perjalanan pulang.
Ya, ternyata memang perkataan itu benar, mengingat aku hidup dalam dunia yang telah rusak, tak ideal, isinya pun demikian–termasuk aku. Tak heran hati ini pun seringkali inginkan banyak hal, harapkan banyak hal, meski pikiran telah sadar bahwa semuanya tak ideal, tak mungkin berjalan sesuai keinginan. Dan, kalau memang hati membutuhkan lebih banyak waktu, tak apa-apa.
Sekilas aku menoleh ke belakang, melihat rombongan keluarga tadi dan menemukan Sang Anak itu juga melihat ke arahku, melambaikan tangan sambil tersenyum teduh. Rasanya tak masuk akal, namun interaksi itu benar-benar menenangkan, seolah Tuhan sendiri yang melihatku dan tersenyum padaku.
Pertanyaan “mengapa” itu belum menemukan jawab, namun aku dikuatkan untuk berharap sekali lagi, berjalan sekali lagi, dengan mengetahui bahwa Tuhan melihatku dan tersenyum padaku di tengah kelamnya derita.
Penulis: Maria Clarissa Putri*
Penyunting: Yemima GP
(*Penulis terpilih sebagai Tiga Penulis Terbaik dari tantangan menulis Natal tahun 2025 bersama Pena Murid dengan tema Membaca Ulang Natal Lewat Wajah-Wajah yang Terlupakan)