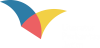Salib adalah simbol yang sarat dengan paradoks. Saat ini, di tengah budaya populer, salib mungkin telah menjadi semacam produk fashion. Seorang selebriti dapat mengenakan aksesori kalung salib hanya untuk mempercantik penampilannya, tanpa ada kaitan dengan pemaknaan agama manapun.
Sulit dibayangkan, bahwa di balik “kegenitan” aksesori salib sebagai pelengkap busana masa kini, sejatinya salib telah menjadi alat bagi salah satu hukuman mati yang paling brutal dan keji dalam sejarah manusia. Inilah paradoks salib pertama: salib saat ini telah menjadi simbol kemewahan lifestyle modern, padahal dahulu adalah simbul kebiadaban.
Pada masa kehidupan Yesus Kristus, salib tidak pernah diperhitungkan sebagai sarana hukuman mati yang beradab dan “layak” bagi bangsa Yahudi. Hukuman mati menurut Hukum Musa atau Taurat adalah dengan pedang (Keluaran 21), dibakar (Imamat 20:14), dan dirajam dengan batu (Ulangan 21:21). Kematian manusia yang digantung adalah satu bentuk kematian terkutuk dan menjijikkan menurut Hukum Taurat (Ulangan 21:23).
Sedangkan bagi bangsa Romawi sendiri, salib sebenarnya merupakan metode eksekusi yang brutal, yang hanya diperuntukkan bagi penjahat-penjahat luar biasa, seperti pemberontak. Warga negara Romawi tidak akan menjalani hukuman biadab ini, karena hukuman salib sendiri diadopsi militer Romawi dari praktik-praktik eksekusi bangsa barbar.
Bagi bangsa Yahudi kematian salib adalah kutukan. Bagi bangsa Romawi yang mengadopsi budaya Yunani, kematian salib adalah kehinaan tak terperikan. Namun, bagi pengikut Kristus sepanjang zaman, salib justru menjadi simbol kemuliaan.
John Stott menulis,
Setidaknya sejak abad kedua dan seterusnya, orang Kristen bukan hanya menggambar, melukis, dan mengukir salib sebagai simbol piktorial dari iman mereka, tetapi juga membuat tanda salib pada diri mereka dan pada orang lain.
Inilah paradoks salib kedua: di balik gambaran kengerian dan kebrutalan sebuah cara untuk menghukum mati manusia, salib telah menjadi cara umat Tuhan merayakan iman mereka dengan penuh kemenangan.
Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menuliskan keyakinannya tentang salib:
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kemuliaan Allah (1Kor. 1:18).
Sejak peristiwa penyaliban Yesus Kristus yang dicatat keempat Injil, setiap orang yang pada dasarnya menjadi seteru Allah melihat salib sebagai kebodohan.
Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap orang yang binasa, akan selalu melihat berita Salib adalah kebodohan. Namun justru bagi orang yang diselamatkan oleh Allah, berita Salib adalah hikmat Allah.
“Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah (1Kor. 1:24).
Inilah paradoks salib ketiga: salib akan menjadi berita kebodohan bagi orang yang binasa, namun ia justru menjadi kekuatan dan hikmat Allah bagi yang diselamatkan.
Di antara ketiga paradoks salib di atas, dimana Anda saat ini dalam menjalani kehidupan iman Anda? Apakah salib hanya sekadar menjadi simbol mati bagi busana atau dekorasi rumah Anda? Ataukah salib saat ini sekadar menjadi simbol religiusitas dan keagamaan Anda, sehingga pada masa-masa peringatan paskah anda ikut berlomba menampilkannya pada akun medial sosial Anda? Atau seperti yang diharapkan Yesus sendiri, salib seharusnya menjadi narasi kemenangan demi kemenangan bagi hidup kita.
Salib seharusnya menjadi kuasa bagi kita untuk mengalahkan dunia serta keterbatasan-keterbatasan diri kita sendiri. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus Kristus sebelum penyaliban-Nya:
Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejaheta dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia (Yoh. 16:33).
Selamat Paskah.
Sebuah refleksi Paskah oleh: Yusuf Deswanto
*) Yusuf Deswanto, M.Div, saat ini melayani di Perkantas Jember, Mas Ucup biasanya dia disapa, adalah salah satu penggagas hadirnya komunitas Pena Murid 4 tahun lalu.